Oleh: Rendi Hidayat, SE., ME.
Dalam tata kelola pemerintahan daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) memiliki posisi strategis sebagai motor administrasi sekaligus penghubung antara kebijakan politik kepala daerah dan sistem birokrasi di bawahnya. Namun posisi ini sering kali disalahpahami sebagai sumber kekuasaan tambahan, sebuah tafsir keliru yang menempatkan Sekda seolah memiliki kewenangan independen di luar garis komando Gubernur.
Ketika persepsi semacam itu menjelma menjadi tindakan administratif yang melangkahi kewenangan kepala daerah, maka sesungguhnya sedang terjadi pergeseran berbahaya dalam tatanan birokrasi: dari sistem yang hierarkis menjadi sistem yang beroperasi atas kehendak personal.
Kasus pembebasan sementara seorang pejabat eselon IV di lingkungan Badan Penghubung Daerah oleh Sekda baru-baru ini menjadi contoh nyata dari persoalan tersebut. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan serius, tidak hanya dari aspek etik dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga dari sisi legalitas keputusan administratif.
Dalam sistem pemerintahan daerah, setiap keputusan kepegawaian, terutama yang bersifat strategis seperti pemberhentian sementara, merupakan bagian dari kewenangan kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Sekda, dalam konteks ini, hanya bertindak sebagai pejabat yang membantu pelaksanaan tugas administratif kepala daerah, bukan sebagai otoritas mandiri yang dapat mengambil keputusan sepihak terhadap pejabat di bawahnya.
Secara hierarkis, pelimpahan kewenangan kepegawaian dari gubernur kepada Sekda diatur secara ketat, dan hanya dapat dilakukan dengan dasar surat keputusan pelimpahan yang eksplisit. Jika pelimpahan tersebut tidak ada, maka setiap tindakan kepegawaian yang dilakukan Sekda tanpa dasar pelimpahan berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan, khususnya prinsip ultra vires, bertindak melampaui kewenangan.
Pelanggaran semacam ini bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi hukum, karena keputusan yang diambil tanpa kewenangan dianggap cacat yuridis dan dapat dibatalkan.
Jika ditinjau dari struktur kelembagaan, Badan Penghubung Daerah hanyalah unit kerja setingkat eselon IIIA di bawah koordinasi Biro Umum dan Administratif. Pejabat yang dibebaskan pun berstatus eselon IV, sehingga tidak berada pada posisi strategis yang menuntut intervensi langsung pejabat setingkat Sekda. Terlebih, proses hukum yang disebut dalam SK tersebut masih berada pada tahap penyelidikan, belum pada tingkat penyidikan. Artinya, secara hukum belum ada penetapan status tersangka terhadap pejabat yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 serta Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020, pembebasan sementara dari jabatan hanya dapat dilakukan apabila ASN telah ditetapkan sebagai tersangka atau tengah menjalani proses hukum yang menghalangi pelaksanaan tugasnya.
Dalam kasus ini, pejabat tersebut tidak berstatus tersangka, tidak ditahan, serta tidak mengalami pembatasan tugas. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum yang membenarkan penerbitan SK pembebasan sementara dimaksud. Karena itu, keputusan pembebasan jabatan ini tidak hanya tidak proporsional, tetapi juga tanpa dasar hukum yang sah.
Lebih jauh, Sekda sendiri telah dimintai keterangan oleh kejaksaan sebagai saksi dalam kasus yang sama. Fakta ini menimbulkan dugaan kuat adanya keterkaitan antara pemeriksaan tersebut. dengankeputusan pembebasan sementara terhadap pejabat eselon IV dimaksud. Jika benar demikian, maka keputusan ini bukan hanya bermasalah secara administratif, tetapi juga sarat potensi konflik kepentingan.
Dalam tata kelola birokrasi yang sehat, seorang pejabat tinggi seharusnya menjaga jarak dari situasi yang menimbulkan persepsi keberpihakan, apalagi menggunakan kewenangan administratif untuk memperkuat posisi personal di tengah proses hukum yang masih berjalan.
Pada akhirnya, kasus ini menjadi cermin dari bagaimana penyalahgunaan persepsi tentang “Otoritas” dapat menggerus prinsip akuntabilitas dalam birokrasi. Sekda, sebagai jabatan karier tertinggi di daerah, semestinya menjadi benteng profesionalisme ASN, bukan bagian dari arena tarik-menarik kekuasaan.
Kewenangan administratif harus dijalankan dalam kerangka hukum yang jelas, bukan sebagai alat legitimasi politik atau personal. Bila hal ini diabaikan, maka reformasi birokrasi hanya akan menjadi jargon tanpa makna, sementara praktik kekuasaan terus berlangsung di balik meja administrasi. [*]
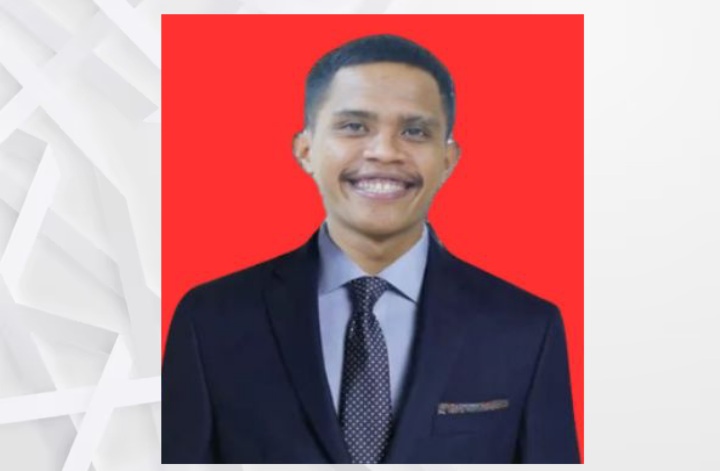








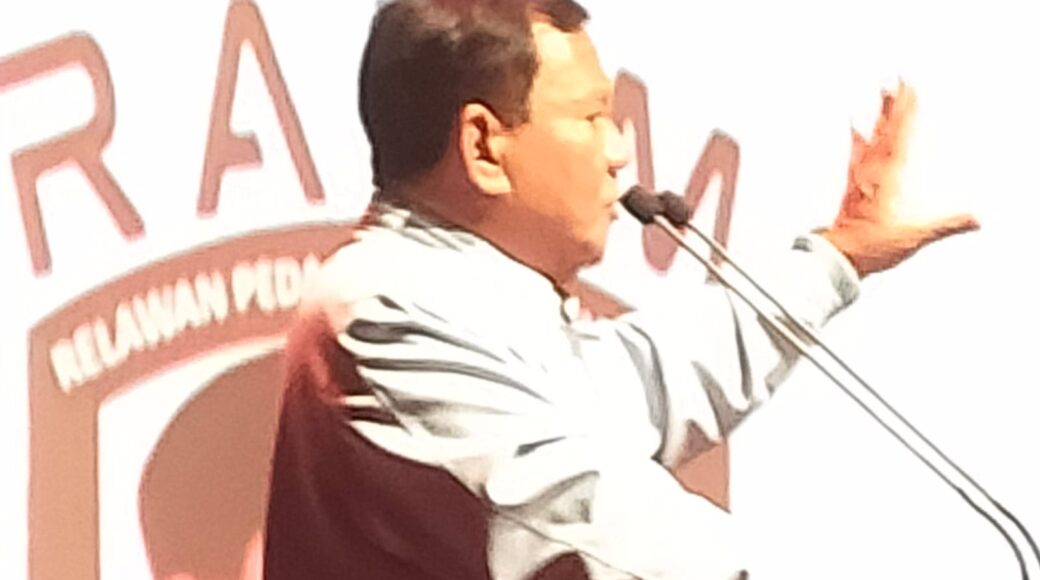

https://shorturl.fm/J4AnD
https://shorturl.fm/x0cAb
https://shorturl.fm/fsq65
https://shorturl.fm/pjlJD
https://shorturl.fm/Tuua1
https://shorturl.fm/Bof3S
https://shorturl.fm/u7ISa
k28l7g
Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice procedures and we are looking to trade strategies with other folks, please shoot me an email if interested.
I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again